PARA Pendiri Negara mendefinisikan identitas ideologi negara dengan melangkah brilliantly mengatasi sekat-sekat primordial.
Apa maksudnya “melangkah jauh mengatasi sekat-sekat primordial”? Artinya, identitas itu:
- tidak dimaknai secara personal, melainkan interpersonal;
- tidak per-golongan atau antargolongan, melainkan keseluruhan;
- tidak agamis, melainkan transendental-kultural-religius;
- tidak rasial, melainkan citarasa bangsa;
- tidak historis dominasi mayoritas, melainkan peradaban kehidupan.
Yang terakhir ini maksudnya Indonesia itu bukan milik Islam (meskipun umat Islam adalah komponen mayoritas), sebab Indonesia toh pernah “dimayoritasi” oleh Hindu atau mereka dengan kepercayaan tradisional.
Artinya, yang bukan Islam pun, dalam perspektif para Pendiri Negara ini, memiliki hak yang sama.
Indonesia ini tidak direbut oleh Islam, melainkan menjadi ruang kehidupan bagi siapa pun untuk bernafas dan bertumbuh serta berkembang, ya Islam, ya Hindu, ya Budha, ya Kristen, Katolik, Konfusius, dan seterusnya. (Alinea ini dikutip dari buku Berfilsafat Politik Kanisius: 2010, hlm. 124).
Dengan demikian “melangkah jauh mengatasi sekat-sekat primordial” juga memaksudkan citarasa sebagai bangsa secara menyeluruh.
Identitas adalah juga realitas yang menjangkau prinsip-prinsip persaudaraan, ketetanggaan, solidaritas, dan dialogalitas. Dalam memikirkan identitas, para Pendiri Negara ini meletakkan fondasi filsafat yang sangat kokoh, yang jauh melampaoi primordialitas.
Dan, ini bukan sebuah pergumulan yang sederhana.
Lagi, menurut Atmodarminto dalam sidang Konstituante 1957, sejarah bangsa Indonesia bukanlah sejarah Islam atau menuju ke-Islam-an.
Sejarah Indonesia adalah sejarah konflik dan rivalitas yang tidak berkesudahan sejak Hindu, Budha, dan tatkala kerajaan-kerajaan Islam. Tidak ada kesatuan dalam raja-raja Islam (Lih. Herbert Feith and Lance Castles, eds., Indonesian Political Thinking 1945-1965, Ithaca and London: Cornell University, 1970, chapter v).
Pidato Atmodarminto memiliki bahasa realis-historis. Pidato itu merupakan salah satu cetusan Pencerahan yang sulit dicari kembarannya dalam sejarah pergerakan politik Indonesia sejak pertama kalinya dijalankan perdebatan tentang ideologi negara hingga saat ini.
Saya menyebutnya: Aufklärung Indonesia.
Di sinilah pentingnya pemahaman diskursus perumusan ideologi bangsa. Aneka rincian gagasan para Pendiri Negara kita adalah filsafat eksistensi societas Indonesia yang menjadi rujukan perennial perjalanan politik bangsa.
Di era Orde Baru nasionalisme mendapat makna baru yang nyaris secara hampir lengkap membingkai keberadaan manusia Indonesia. Orde Baru kerap disebut orde pembangunan.
Tetapi, era ini menyisakan sebuah panorama aneka drama pilu yang gandeng dengan etika utilitarian-machiavellian. Diawali dengan peristiwa tahun 1965. Jargon “membersihkan komunisme sampai seakan-akarnya” telah melindas prinsip-prinsip kemanusiaan tanpa rasa bersalah sedikit pun.
Aneka pemberontakan di Aceh, Maluku dan Papua dimaknai secara simplistis sebagai yang melawan ideologi kesatuan bangsa. Demikian juga dengan berbagai protes ketidak-puasan atas manipulasi, korupsi, kolusi, nepotisme yang merajalela di lingkaran kekuasaan.
Nasionalisme di era Orde Baru tampak gemilang di luar, tetapi keropos di dalam. Nasionalisme yang kerap dimaknai sebagai aktivitas bela negara, dalam banyak praktik, telah meminggirkan rasa humanisme dalam aneka cetusannya.
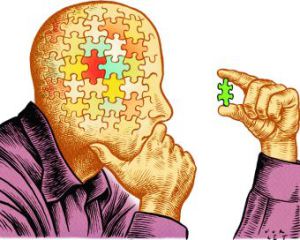
Societas kritis
Societas yang terbentuk pada periode ini saya sebut “societas kritis”.
Societas kritis memiliki dua makna sekaligus:
- bangsa kita memang berada dalam disposisi critical dalam maksud senantiasa bergumul dengan kerawanan kediktatoran dan kekejaman otoritas di satu pihak;
- tetapi di lain pihak, societas ini juga menampilkan keberanian-keberanian untuk tidak berhenti mengkritik kebobrokan.
Kini, di era milenia baru, societas Indonesia terkadang masih ada dalam kegamangan. Ketika globalisasi, multikulturalisme, pluralisme, postmodernisme campur-baur membangun peradaban tata dunia baru, Indonesia di sana sini terseok oleh aneka konflik kepentingan primordial.
Maka, konsep nasionalisme kita saat ini haruslah lebih mengedepankan skema-skema pembentukan societas kolaboratif yang menjunjung tinggi keanekaragaman dan tidak mereduksinya dalam keseragaman.
Kita harus menjadi sebuah societas yang dinamis dalam upaya-upaya kolaborasi konkret, cerdas dan kreatif. Satu sama lain dengan siapa saja. Membangun keutuhan bangsa manusia.
Untuk maksud ini, saya merekomendasikan pembaca membaca buku Kearifan Lokal Pancasila: Butir-Butir Filsafat Keindonesiaan, Kanisius :2015).
Kearifan lokal
Yang dimaksud kearifan lokal ialah filsafat yang hidup di dalam hati masyarakat, berupa kebijaksanaan akan kehidupan, way of life, ritus-ritus adat, dan sejenisnya. (bdk. Pengantar buku Kearifan Lokal Pancasila: Butir-Butir Filsafat Keilahian, Kanisius: 2015).
Kearifan lokal (local wisdom) merupakan produk berabad-abad yang melukiskan kedalaman batin manusia dan keluasan relasionalitas dengan sesamanya serta menegaskan keluhuran rasionalitas hidupnya.
Kearifan lokal memiliki kedalaman dan cetusan nyata yang indah berupa:
- relasi dengan Tuhan atau konsep tentang Tuhan;
- relasi dengan alam atau dunia;
- relasi dengan sesamanya dan hidup bersama;
- bagaimana konsep kemanusiaan tumbuh dan berkembang;
- bagaimana pengertian tentang kebersatuan dihayati dan dihidupi;
- bagaimana kebersamaan dalam hikmat dan kebijaksanaan ditata;
- bagaimana gambaran mengenai keadilan diwujudnyatakan.

Kearifan lokal tersembunyi dalam tradisi hidup sehari-hari, dalam mitologi, dalam sastra yang indah, dalam bentuk-bentuk ritual penghormatan atau upacara adat, dalam wujud nilai-nilai simbolik bentuk rumah (tempat tinggal), dalam bahasa dan kebudayaan kesenian, dan dalam tata kehidupan “lokalitas” indah lainnya.
Kearifan lokal memiliki karakter yang lekat dengan locus (tempat), yang darinya ditarik ajektif, local (yang berkaitan dengan tempat).
“Locus” dalam filsafat tidak sekedar mengatakan sudut pandang geografis, melainkan kehidupan manusia yang berkaitan dengan “wilayah”.
Tempat tinggal di suatu wilayah tidak hanya berupa dataran atau pegunungan atau pinggiran pantai, atau hutan atau sawah, melainkan mengurai suatu kebijaksanaan khas.
Kebijaksanaan berupa produk “relasionalitas” manusia dengan alam tempat dia bertumbuh dan berkembang. Jadi, “lokalitas” juga memaksudkan “relasionalitas” manusia dengan alam, Tuhan yang mengatasi hidupnya, dan sesamanya.
“Relasionalitas” merupakan serangkaian relasi sehari-hari manusia yang berlanjut dalam cetusan-cetusan kesadaran yang mendalam.

Masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil, misalnya, memiliki kesadaran yang mendalam akan bagaimana kepemilikan tanah diatur sedemikian rupa sehingga muncul kearifan-kearifan yang mencegah monopoli.
Semua bisa memiliki semua, agar tidak ada yang berkekurangan; dan jangan sampai satu atau beberapa mendominasi kepemilikannya.
Demikianlah, “relasionalitas” menjadi suatu bentuk “rasionalitas” hidup bersama.
Konteks hidup sehari-hari berupa alam, “tanah”, “air”, “laut”, “hutan”, atau “sawah”, “pohon”, “binatang”, “sungai”, “punden” (sumber air), atau sekitar itu menjadi pula konteks “rasionalitas” yang menjadi milik masyarakat setempat.
Local wisdom
Relasi mereka dengan konteks hidup itu kerap dirupakan dalam mitos, legenda, atau simbol-simbol bangunan atau alam atau yang lain yang di dalamnya melahirkan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang memesonakan.
Kebijaksanaan inilah yang disebut local wisdom.
Karena mitos bukanlah kisah khayalan (atau cerita untuk pengentar tidur), melainkan merupakan suatu “rasionalitas” dalam bentuk perdananya yang merupakan produk relasionalitas manusia dengan alam hidupnya.
“Relasionalitas” manusia dengan konteks hidupnya memiliki fondasi kesadaran akan “Yang Suci” atau “Yang Mengatasi”.
Jadi, “Yang suci” tidak diasalkan dari ajaran doktrin institusi religius atau agama, melainkan berasal dari “kesadaran batin” manusia.
“Relasionalitas” memiliki pula fondasi kesadaran “dunia batin” dalam maksud relasi manusia tidak sekedar berada dalam pertimbangan praktis atau pragmatis.

Ketika manusia-manusia yang tinggal di pesisir pantai melihat laut, produk penglihatannya ialah bahwa laut menjadi seperti seorang “ibu” bagi mereka.
Sebab, samudera memungkinkan mereka bisa hidup, setiap hari mengambil ikan-ikan yang membuat mereka tidak kekurangan apa-apa.
Upacara “melarung” persembahan ke laut, misalnya, tidak boleh disimak sebagai tindakan yang bertentangan dengan rasionalitas. Kebalikannya, justru ritual melarung hasil bumi ke laut menjadi seolah-olah ucapan syukur dan terimakasih kepada “ibu” yang terus memelihara mereka.
“Kekuatan” laut dahsyat, bukan karena bencananya, melainkan karena “pemeliharaan” (seolah seperti seorang “ibu”) kepada hidup mereka secara terus-menerus. Kesadaran inilah yang disebut kesadaran “dunia batin.”
Dalam kebijaksanaan Jawa, misalnya, “dunia batin” luas sekali lebih luas daripada samudera dan dalam sekali lebih dalam dari laut yang paling dalam. Artinya, kedalaman dan keluasan “dunia batin” hidup manusia sungguh tak terselami.
Apa yang terungkap, tercetus, tersembul dan berhasil diuraikan oleh akal budi manusia hanyalah bagaikan “setetes” air di lautan.
Demikianlah juga dengan butir-butir kearifan yang tersaji di dalam buku Kearifan Lokal ~ Pancasila: Butir-butir Filsafat Keindonesiaan – sungguh pun diupayakan memiliki persiapan yang cukup lama – tetap tidak mampu menjangkau secara merata “samudera” kearifan yang membentang luas wilayah Indonesia. (Bdk. Menurut Ensiklopedi Suku-Suku Bangsa Indonesia karya Dr. Junus Melalatoa: Bangsa Indonesia terdiri dari 931 suku seperti dikutip Prof. Dr. Koentjaraningrat dalam Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, Jakarta: Djambatan, 1997, viii).
Terasa sedikit dalam jumlah aneka kearifan lokal yang disuguhkan dalam buku tersebut merepresentasi semua suku Indonesia. Sungguh pun demikian semoga memberikan “butir-butir” yang perlu diteruskan untuk diteliti dan dikembangkan.
Para penulis merupakan pribadi-pribadi yang “merayakan” kedalaman local wisdom di satu pihak. Tetapi di lain pihak juga diguyur oleh keprihatinan dan kegelisahan karena gejala-gejala “kedangkalan” kehidupan bangsa dan negara. (Berlanjut)










































