
MARI kita bicara tentang trauma, kemarahan, dan tanggungjawab Komunitas Iman terhadap anak yang terluka.
Peristiwa tragis peledakan di SMAN 72 Jakarta mengguncang hati banyak orang. Tindakan yang dilakukan oleh seorang remaja -yang juga menjadi korban dari ledakan tersebut- mengundang banyak pertanyaan mendalam. Yakni, bagaimana mungkin seorang siswa yang seharusnya masih dalam masa belajar dan bermain sampai pada titik di mana ia ingin melukai dirinya sendiri dan orang lain?
Kasus ini bukan sekadar masalah kriminal atau keamanan sekolah. Ini menyingkap lapisan luka yang lebih dalam – luka batin remaja modern yang hidup di tengah tekanan sosial, kesepian emosional, dan kehilangan arah makna.
Kajian pastoral ini berusaha menelusuri akar-akar permasalahan dari perspektif iman Katolik, psikologi perkembangan, dan tanggungjawab pastoral Gereja terhadap jiwa-jiwa muda yang terluka.

1. Dimensi psikologis: Remaja di tengah tekanan emosi dan identitas
a. Masa remaja sebagai krisis identitas
Menurut Erik Erikson, masa remaja adalah tahap identity vs. role confusion – saat seseorang mencari jawaban atas pertanyaan eksistensial: “Siapa aku? Untuk apa aku hidup?” Jika remaja gagal menemukan makna dan dukungan sosial yang memadai, ia bisa jatuh pada kebingungan, frustrasi, atau pemberontakan destruktif.
b. Luka psikologis yang tidak terlihat
Banyak remaja menanggung luka batin tersembunyi: penolakan, perundungan, perceraian orangtua, atau kehilangan kasih sayang. Luka itu sering tidak tertangani, karena dunia dewasa jarang mau mendengar. Akibatnya, rasa sakit itu berubah menjadi kemarahan pasif (withdrawal, isolasi) atau kemarahan aktif (agresi, kekerasan).
c. “Peledakan” sebagai gejala akumulatif
Perilaku ekstrim seperti peledakan bukanlah tindakan spontan, melainkan puncak dari akumulasi tekanan psikis. Remaja yang terisolasi, dihina, dan tidak memiliki ruang ekspresi akhirnya mencari “kendali” dalam bentuk tindakan simbolis: melukai diri sendiri atau lingkungannya. Dalam psikologi, hal ini disebut acting out – mengekspresikan penderitaan batin lewat tindakan fisik yang destruktif.
2. Dimensi keluarga: Relasi yang membentuk atau melukai
a. Keluarga sebagai sekolah kasih
Keluarga adalah “Gereja Mini” (Ecclesia domestica), tempat anak pertama-tama belajar mencintai dan dicintai. Jika suasana keluarga dingin, penuh tekanan, atau tanpa komunikasi, anak tidak menemukan tempat aman bagi jiwanya. Ia belajar bahwa dunia adalah tempat yang keras dan kasih hanyalah konsep kosong.
b. Pola Relasi yang membentuk luka
Beberapa pola keluarga yang sering menimbulkan luka mendalam:
- Otoritarian tanpa kehangatan: anak tumbuh dalam ketakutan, bukan kasih.
- Permisif tanpa batas: anak tidak mengenal tanggung jawab, lalu frustrasi saat dunia menolak kehendaknya.
- Kehadiran fisik tanpa kehadiran emosional: orang tua ada, tetapi hati mereka jauh.
Semua pola ini dapat menciptakan remaja dengan emosi rapuh, haus validasi, dan mudah meledak saat tertolak.
c. Kebutuhan akan restorasi relasi
Pemulihan keluarga bukan hanya tugas psikologis, tetapi juga tugas pastoral. Gereja perlu mendampingi keluarga agar relasi antaranggota dihidupi dalam semangat communio—saling mendengar dan saling meneguhkan dalam kasih Kristus.

3. Dimensi sosial dan sekolah: Bullying dan krisis solidaritas
Sekolah semestinya menjadi ruang aman bagi pertumbuhan, tetapi sering kali berubah menjadi arena survival. Fenomena bullying—baik verbal, fisik, maupun digital—menghancurkan rasa harga diri remaja. Dalam jangka panjang, korban bisa menginternalisasi pesan negatif seperti:
- “Aku tidak berharga.”
- “Tidak ada yang peduli padaku.”
Ketika pesan ini diulang terus-menerus, jiwa mulai percaya bahwa keberadaannya tidak berarti. Di titik ini, tindakan ekstrim menjadi “cara terakhir” untuk membuat dunia memperhatikan.
Krisis solidaritas ini menandakan hilangnya nilai belas kasih (compassio) di antara pelajar. Sekolah, Gereja, dan keluarga mesti bekerja sama menumbuhkan budaya saling menghargai—bukan sekadar disiplin moral, melainkan spiritualitas persekutuan.
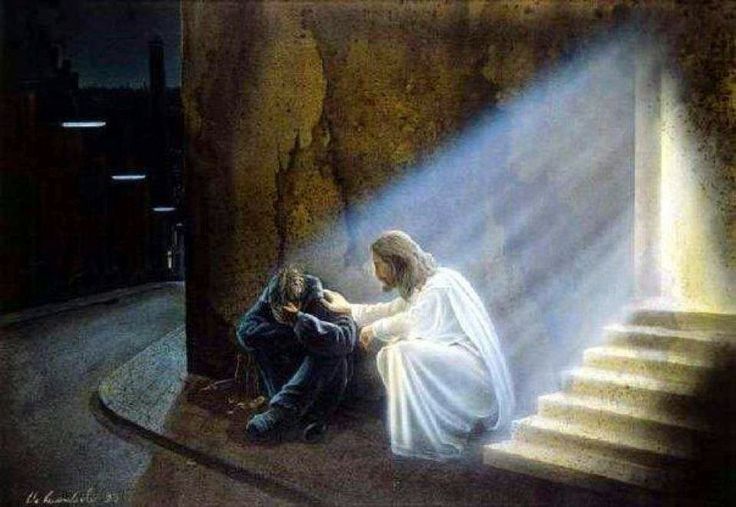
4. Dimensi teologis: Dosa, luka, dan penebusan
a. Setiap luka adalah tempat Allah bekerja
Iman Katolik mengajarkan bahwa Allah hadir bahkan di tengah penderitaan. Kristus yang disalibkan bukan hanya menebus dosa, tetapi juga menyentuh luka manusia yang terdalam. Maka, pastoral bagi remaja yang terluka bukan pertama-tama tentang menghukum, melainkan menyembuhkan dengan kasih Kristus.
b. Dosa struktural: Ketika masyarakat turut bersalah
Ketika komunitas membiarkan perundungan, kekerasan verbal, dan penghinaan berakar, masyarakat turut menanam “benih dosa struktural.” Tindakan ekstrem seorang anak bisa menjadi cermin dari kegagalan bersama—keluarga, sekolah, dan Gereja – yang kurang menjadi ruang kasih.
c. Kristus sebagai model restorasi
Kristus mengampuni bahkan dari atas salib: “Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.” (Luk 23:34)
Pendekatan pastoral yang berakar pada Injil mengajak kita mengganti rasa takut dengan empati, dan mengubah penghakiman menjadi pendampingan.
5. Dimensi pastoral: Jalan pemulihan dan pencegahan
a. Gereja sebagai rumah penyembuhan
Komunitas iman perlu menjadi safe space – tempat remaja merasa diterima tanpa syarat dan didengar tanpa dihakimi. Pendamping remaja perlu dilatih bukan hanya dalam doktrin, tetapi juga dalam pendampingan psiko-spiritual: mendengarkan dengan empati, membaca tanda-tanda luka, dan menyalurkan remaja kepada konselor profesional bila perlu.
b. Pastoral preventif
Beberapa langkah konkrit:
- Membangun budaya mendengar di keluarga dan sekolah.
- Mengadakan kelompok sharing iman bagi remaja dengan fokus pada pengalaman hidup nyata, bukan hanya teori moral.
- Mengintegrasikan pendidikan emosional dan iman. Remaja perlu belajar bahwa marah, kecewa, atau terluka adalah bagian dari kemanusiaan yang bisa dipersembahkan kepada Allah.
- Menghadirkan figur teladan iman muda—remaja Katolik yang berani hidup dalam kasih, bukan kekerasan.
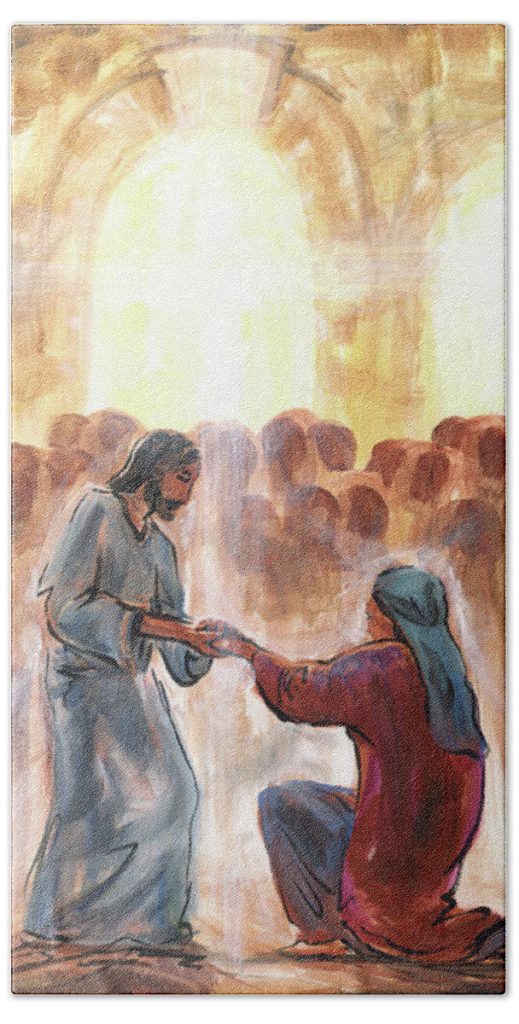
c. Pendampingan pasca-tragedi
Setelah peristiwa traumatis, penting untuk mengadakan liturgi penyembuhan atau doa tobat dan pengampunan yang melibatkan seluruh komunitas sekolah. Liturgi ini bukan hanya doa, melainkan sarana membangun kembali rasa aman dan solidaritas.
Penutup: Misi Gereja bagi anak yang terluka
“Ia telah mengutus Aku untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya.” (Luk 4:18)
Tugas Gereja bukan hanya menuntun orang ke surga, tetapi juga menyembuhkan hati yang hancur di bumi. Setiap anak yang terluka adalah wajah Kristus yang menderita. Ketika Gereja -melalui keluarga, sekolah, dan komunitas- mendengar jeritan batin mereka, kasih Allah menjadi nyata.
Tragedi seperti di SMAN 72 menjadi panggilan profetis bagi seluruh umat Katolik: untuk membangun dunia yang lebih penuh kasih, empati, dan pengampunan.
Bukan dengan menuduh, tetapi dengan mendekap;
bukan dengan menghakimi, tetapi dengan menyembuhkan;
bukan dengan menakuti, tetapi dengan mengasihi—
seperti Kristus sendiri.









































