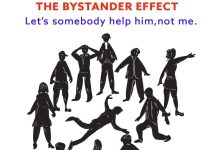Selasa, 4 Oktober 2025
Rm. 12:5-16a
Mzm. 131:1,2,3
Lukas 14:15-24
ADA kalanya bahaya terbesar dalam hidup rohani bukan terletak pada dosa-dosa besar yang mencolok, bukan pada pembunuhan, pencurian, atau penyelewengan moral yang mudah kita kenali sebagai kejahatan.
Bahaya terbesar justru datang diam-diam, tanpa suara, tanpa gegap gempita: ketika hati kita perlahan-lahan dipenuhi oleh hal-hal duniawi hingga tak ada lagi ruang bagi Allah.
Kita sibuk, bahkan mungkin dengan hal-hal yang baik: pekerjaan, keluarga, pelayanan, mimpi, dan ambisi.
Namun di tengah semua itu, hati bisa menjadi seperti rumah yang terlalu penuh barang: setiap sudutnya dijejali keinginan, kekhawatiran, dan pencapaian, hingga Sang Pemilik sejati tak lagi mendapat tempat untuk berdiam.
Bahaya terbesar bukan hanya ketika kita melawan Allah, melainkan ketika kita tak lagi merindukan-Nya. Bukan hanya ketika kita jatuh dalam dosa, melainkan ketika kita merasa cukup tanpa rahmat-Nya.
Dalam bacaan Injil hari ini, kita dengar demikian, “Tetapi mereka semua minta dimaafkan. Yang pertama berkata, Aku baru membeli ladang dan harus pergi melihatnya; aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, Aku baru membeli lima pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya; aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, Aku baru saja menikah, dan karena itu aku tidak dapat datang.”
Undangan itu istimewa, simbol kasih karunia Allah yang memanggil manusia untuk masuk dalam persekutuan dengan-Nya.
Undangan itu, mereka tolak. Menariknya, alasan mereka tampak wajar dan masuk akal: membeli ladang, mencoba lembu, dan baru menikah.
Tidak ada yang jahat dalam hal-hal itu. Semuanya adalah bagian dari hidup yang normal. Tetapi di situlah letak bahayanya.
Sering kali kita tidak menolak Allah dengan keburukan, melainkan dengan hal-hal baik. Kita tidak berkata, “Aku tidak mau datang,” tetapi, “Tuhan, aku sibuk dulu.”
Kita tidak berpaling karena benci, tetapi karena prioritas kita bergeser. Ladang, lembu, dan pernikahan melambangkan dunia kerja, harta benda, dan relasi, tiga hal yang baik, namun dapat menjadi berhala halus ketika menempati tempat yang seharusnya hanya bagi Allah.
Tuhan tidak menentang pekerjaan, kekayaan, atau keluarga. Ia justru menghendaki kita setia dan bertanggung jawab. Namun, Ia menginginkan agar semua itu tidak menghalangi undangan kasih-Nya.
Ketika hati kita terlalu terikat pada hal-hal duniawi, kita kehilangan kepekaan terhadap undangan rohani yang datang dalam keheningan: undangan untuk berdoa, untuk melayani, untuk bersyukur, untuk hadir di hadapan-Nya.
Mereka yang menolak undangan itu pada akhirnya kehilangan sukacita perjamuan. Demikian pula kita, setiap kali kita menunda waktu doa, menolak kesempatan berbuat kasih, atau mengutamakan urusan dunia tanpa ruang bagi Allah, kita sedang berkata hal yang sama: “Tuhan, aku minta dimaafkan.”
Bagaimana dengan diriku?
Apakah hatiku masih peka terhadap panggilan kasih-Nya di tengah kesibukan hidup?