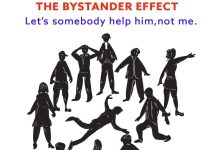Rabu, 5 November 2015
Rm. 13:8-10.
Mzm. 112:1-2,4-5,9.
Luk. 14:25-33
KETIKA kita berbicara tentang memberikan totalitas hidup kepada Tuhan, itu bukan sekadar soal melakukan banyak hal untuk-Nya, melainkan menyerahkan seluruh keberadaan kita kepada Dia.
Totalitas hidup mencakup waktu, tenaga, pikiran, bahkan impian yang paling pribadi. Semua itu kita letakkan di altar kasih Allah, bukan sebagai kehilangan, melainkan sebagai persembahan.
Dalam dunia yang serba cepat dan menuntut hasil, kita sering tergoda untuk menyisakan sebagian hidup bagi Tuhan, memberi Dia waktu ketika sempat, tenaga ketika tidak lelah, pikiran ketika tenang, dan impian ketika sudah tercapai.
Tuhan Yesus tidak menginginkan sisa. Ia menginginkan seluruh hati kita. Ia telah lebih dahulu memberikan segalanya bagi kita, hidup-Nya, darah-Nya, dan kasih-Nya yang tanpa batas.
Ketika kita rela mempersembahkan hidup secara total, kita masuk ke dalam misteri sukacita sejati. Sukacita itu bukan berarti hidup menjadi mudah, tetapi karena kita tidak lagi berjalan sendiri.
Di tengah perjuangan, kita sadar bahwa Yesus berjalan bersama kita. Ketika kita lelah, Dia menopang. Ketika kita kehilangan arah, Dia menuntun. Ketika kita jatuh, Dia mengangkat.
Dalam bacaan Injil hari ini kita dengar demikian, “Jikalau seorang datang kepada-Ku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, isterinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi murid-Ku.”
Menjadi murid Kristus berarti menempatkan kasih kepada Allah di atas segala-galanya. Artinya, cinta kita kepada orang tua, pasangan, anak, atau diri sendiri tidak boleh melampaui cinta kita kepada Tuhan.
Kasih kepada Tuhan adalah sumber dari segala kasih sejati. Bila kita mencintai Tuhan secara total, maka kita pun mampu mengasihi sesama dengan murni, bukan karena ego, tetapi karena kasih ilahi yang mengalir melalui kita.
Yesus menuntut prioritas. Ia ingin agar hati kita tidak terbagi. Sebab hati yang setengah untuk Tuhan, setengah untuk dunia, akan mudah goyah dan rapuh.
Ketika Tuhan menjadi yang pertama, maka segala relasi dan keputusan hidup kita akan menemukan keseimbangannya.
Kasih kepada keluarga tidak hilang, justru menjadi semakin tulus karena berakar pada kasih Tuhan sendiri.
Yesus juga mengingatkan agar kita siap melepaskan segala sesuatu yang menghalangi kita mengikut Dia, bahkan diri kita sendiri.
Kadang ego, ambisi, atau rasa nyaman menjadi penghalang untuk menjadi murid sejati.
Maka, “membenci nyawanya sendiri” berarti rela menyangkal diri, agar kehendak Allah terjadi dalam hidup kita.
Bagaimana dengan diriku?
Apakah Yesus sungguh menjadi pusat kasih dan prioritas dalam hidupku?