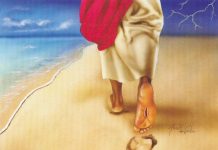DALAM sejarah hidup manusia, kita sudah mengalami apa yang menjadi peran agama. Dalam konteks Gereja Katolik, peran agama itu digambakan sebagai Tria Munera Christi (Tiga Tugas Kristus) yaitu menguduskan (Imam), memimpin (Raja) dan mengingatkan (Nabi).
Dalam tulisan ini, kita akan memfokuskan diri pada peran kenabian sebagai salah satu peran kunci Gereja. Dalam Kitab Suci, suara kenabian digambarkan demikian:
“Ada suara yang berseru-seru, ‘Persiapkanlahdi padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlahdi padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup,dan setiap gunung dan bukit diratakan; tanah yang berbukit-bukitharus menjadi tanah yang rata,dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran.” (Yes 40: 3-4).
Kontekstualisasi dari teks ini di dalam Perjanjian Baru terdapat di dalam kisah St. Yohanes Pembaptis yang mengatakan, “Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun: Luruskanlah jalan Tuhan – seperti yang telah dikatakan nabi Yesaya.” (Yoh 1: 23).
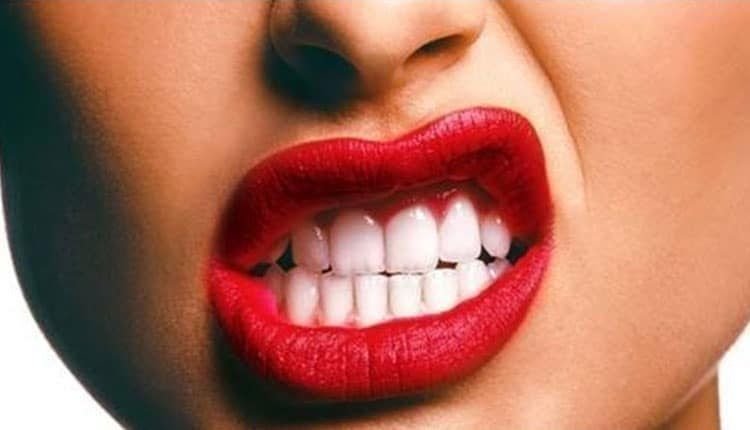
Kita tahu bagaimana nasib Yohanes Pembaptis, ditangkap dan akhirnya meninggal dengan cara dipenggal. Namun, kita tidak boleh melupakan kenyataan bahwa Herodes senang mendengarkan kata-kata Yohanes Pembaptis hingga ia tidak akan memenggal kepala Sang Nabi itu kalau tidak termakan omongannya sendiri pada saat pesta ulang tahunnya.
Di sana dikatakan, “sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu, bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia.” (Mark 6: 20).
Kata “segan” yang dipakai di situ menunjukkan bahwa sebenarnya Herodes, pemimpin yang kejam itu, tetap memiliki dorongan untuk berbuat baik. Dari situ kita belajar bahwa dalam situasi sesulit apa pun suara kenabian tetap harus diutarakan. Mungkin suara kenabian itu membawa risiko, tetapi bukankah demi sebuah kebaikan, iesiko besar pun layak untuk diambil.

Lembaga pendidikan dan keagamaan
Dunia tidak boleh menjadi tempat di mana orang hanya mengabdi kekuasaan dan rasa aman, melainkan tempat di mana suara-suara kebenaran dinyatakan.
Dalam konteks masyarakat modern, pesan-pesan ini diwakili oleh institusi-institusi yang memang berjuang dan lahir sebagai penjaga norma dan etika kebenaran.
Kalau boleh saya menunjuk, institusi-institusi tersebut adalah lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan.Di dalam kedua bidang tersebut, Gereja Katolik sudah sejak lama mengabdikan dirinya.
Gereja Katolik pasca pilpres
Saya menulis kisah di atas, di tengah kegundahan beberapa umat yang merasa bahwa Gereja Katolik dan Perguruan Tinggi Katolik sudah “salah” dalam mengambil sikap di tengah-tengah perhelatan Pemilu 2024. Institusi-institusi yang bernaung di bawah Bunda Gereja yang Kudus tersebut dianggap keliru. Karena telah menyuarakan perlawanan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di seputaran Pemilu 14 Februari 2024 lalu.
Ada pula yang menganggap bahwa langkah yang diambil termasuk langkah yang membahayakan bagi keberadaan Gereja di masa yang akan datang. Tidak sedikit pula yang mengatakan bahwa suara Gereja tidak didengar karena dalam survey Litbang Kompas ditemukan bahwa ada banyak umat Katolik yang memilih pihak yang dituding curang oleh institusi-institusi Gereja.

Paus Fransiskus: Jadi masalah, ketika suara Gereja tidak signifikan
Hal ini mengingatkan saya kepada pesan Paus Fransiskus di dalam rangkaian kunjungannya di Maroko, Afrika Barat.
Beliau mengatakan, “Yang menjadi masalah bukanlah ketika kita sedikit dalam hal jumlah, tetapi ketika kita menjadi tidak signifikan.”
Bagi saya pilihan yang tersedia bagi Gereja Katolik pada masa Pemilu 2024 kemarin adalah untuk menyampaikan suara kenabiannya. Tidak ada pilihan untuk diam, karena memang situasi yang mengharuskan kita berbicara. Bahwa akhirnya suara itu tidak didengarkan oleh sebagian besar orang, bukankah itu sudah menjadi nasib Nabi dari zaman ke zaman.
Betapa tidak signifikannya kehadiran moralitas Gereja saat terjadi pelanggaran-pelanggaran di depan mata dan kita hanya diam saja. Mungkin dalam perjalanan ke depan Gereja harus berjuang lebih keras, tetapi itu adalah pilihan yang lebih baik.
Dalam hal ini, kita bisa berkaca pada pesan Paus Fransiskus, “Saya lebih menyukai Gereja yang memar, terluka dan kotor karena telah keluar di jalan-jalan; daripada Gereja yang sakit karena menutup diri dan nyaman melekat pada rasa amannya sendiri. Saya tidak menginginkan Gereja yang berambisi menjadi pusat dan berakhir dengan terperangkap dalam jerat obsesi dan prosedur.” (EG 49).
Kala tidak bersuara ketika ada hal yang tidak benar di tengah masyarakat, kita akan kehilangan suara kenabian kita.

Yesus berpesan demikian:
“Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi.
Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu.
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga.” (Mat 5: 13-16).
Dari sini, rasanya pilihan sikap untuk menyuarakan suara kenabian adalah pilihan sikap yang tepat di tengah pergulatan bangsa. Mungkin akan ada risiko, tetapi Gereja memang hadir bukan untuk sekedar mengamankan diri, melainkan hadir sebagai suara kenabian yang melibatkan resiko di dalamnya.
Mungkin inilah yang dimaksud sebagai jalan terjal kenabian yang memang harus diambil oleh Gereja Indonesia bersama saudara-saudari seperjuangannya dari agama dan kepercayaan lain.
Martinus Joko Lelono Pr
Imam diosesan Keuskupan Agung Semarang; pengajar Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma.